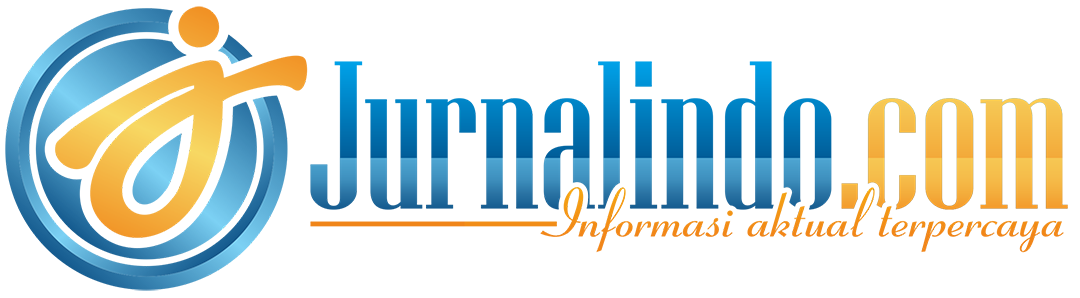Jakarta, 2 September 2025 — Gelombang aksi unjuk rasa yang merebak sejak 25 Agustus 2025 telah menelan korban jiwa. Komnas HAM mencatat sedikitnya 10 orang tewas dalam rentang satu pekan demonstrasi.
Dari data yang dihimpun, korban berasal dari berbagai latar belakang: mahasiswa, pekerja ojek online, pegawai negeri, hingga pelajar. Mereka semua adalah orang yang tak bersalah.
Tragedi ini meninggalkan jejak luka mendalam: ada yang tewas akibat kendaraan taktis, terjebak kebakaran, dikeroyok massa, bahkan meninggal dengan luka memar misterius.
Bagi keluarga korban, peristiwa ini bukan sekadar angka. Ada ibu yang kehilangan anak sulungnya, ada istri yang mendadak menjadi janda, ada adik kecil yang menunggu kakaknya pulang tanpa pernah tahu bahwa sosok yang ditunggu takkankembali. Tangisan dan duka itu nyata, tetapi negara seakan memilih bungkam.
Pertanyaan yang Menggantung di Udara
Hingga kini, proses hukum yang jelas belum terlihat. Pertanyaan besar menggantung di udara dan terus menuntut jawaban:
Tanpa jawaban yang terang, publik menilai kematian mereka hanyalah buah dari kekerasan negara yang melampaui hukum kepada rakyatnya sendiri.
Rakyat yang memiliki sumber daya alam, yang kekayaannya dikelola oleh negara.Rakyat yang menggaji aparat melalui pajak. Rakyat yang memberi fasilitas, kendaraan, bahkan senjata yang kini justru digunakan untuk melawan mereka sendiri.
Dan siapa yang harus bertanggung jawab atas hilangnya nyawa mereka? Siapa yang memberi perintah, siapa yang menugaskan, dan siapa yang menutup mata?
Satu Nyawa Pun Terlalu Mahal
“Satu Nyawa Pun Terlalu Mahal. Bahkan satu tetes darah pun tidak boleh ada.” Dalam negara hukum, satu nyawa manusia pun tidak boleh dihilangkan tanpa proses yang sah. Begitu juga dalam agama apapun.
Namun kenyataannya, puluhan orang ditangkap secara sewenang-wenang, ratusan terluka, dan 10 orang sudah tak bernyawa. Situasi ini memunculkan tudingan keras: aparat telah membantai rakyatnya sendiri. Rakyatnya yang belum jelas kesalahannya.
Lebih memilukan lagi, para korban bukanlah figur besar yang berkuasa. Mereka hanyalah rakyat biasa, yang datang ke jalan dengan harapan aspirasinya didengar. Mereka tidak memiliki pelindung politik, tidak punya media untuk membela diri, dan akhirnya hanya meninggalkan nama di daftar panjang korban tragedi bangsa.
Di saat yang sama, kita melihat ironi pahit. Koruptor kelas kakap, bandar narkoba, bahkan teroris besar kerap lolos dari hukuman mati. Mereka bisa hidup di balik jeruji dengan fasilitas “manusiawi”.Sebagian bahkan masih bisa mengendalikan kekuasaan dan menumpuk uang hasil kejahatan.
Sebaliknya, rakyat kecil yang bahkan belum jelas kesalahannya justru meregang nyawa di jalanan.
Disaat mereka menyuarakan hak rakyat, menyampaikan aspirasi, dan melawan kesewenang-wenangan aparatur negara, justru nyawa mereka melayang. Ironisnya, yang mereka suarakan bukan hanya untuk diri mereka, melainkan untuk kita semua. Bahkan bisa jadi, suara mereka juga mewakili jeritan hati dari mereka yang kini menghilangkan nyawa rakyat.
Kemanusiaan Terkikis, Nurani Hilang
Kekerasan dalam demo ini tidak bisa dilepaskan dari permainan politik dan kepentingan elit. Narasi publik kini terbelah: sebagian membenarkan tindakan keras aparat demi stabilitas, sebagian lain menilai tragedi ini sebagai bukti matinya nurani bangsa.
“Semua hanya dilihat dari kacamata politik. Tidak ada lagi nurani di negeri ini. Terutama di kalangan pejabat, tokoh, dan elit,” ujar salah satu pengamat HAM.
Tragedi ini bukan sekadar soal hukum, melainkan soal jatuhnya martabat bangsa. Bagaimana dunia internasional akan memandang Indonesia ketika rakyatnya sendiri dibungkam dengan cara brutal? Bagaimana generasi muda akan menaruh kepercayaan kepada negaranya, jika yang mereka lihat hanya kekerasan tanpa keadilan?
Banyak yang kini bertanya-tanya: apakah demokrasi di negeri ini hanya sebatas tulisan di undang-undang? Apakah kebebasan berpendapat hanya berlaku di atas kertas, sementara di lapangan suara rakyat dibayar dengan peluru dan gas air mata?
Luka yang Tak Boleh Menjadi Biasa
Di tengah hiruk pikuk politik, ada sebuah bahaya besar: tragedi semacam ini dianggap wajar, bahkan normal. Jika nyawa rakyat terus melayang tanpa proses hukum yang jelas, lama-kelamaan publik bisa terbiasa. Dan ketika masyarakat terbiasa, maka kekerasan akan menjadi budaya.
Itulah yang harus dicegah. Karena sekali rakyat percaya bahwa kekerasan negara adalah hal lumrah, maka habislah makna demokrasi, habislah makna hukum, habislah makna kemanusiaan.
Sejarah bangsa ini sudah cukup kelam. Dari tragedi 1965, 1998, hingga berbagai kasus penembakan misterius, kita melihat pola yang sama: rakyat yang tak bersalah menjadi korban, sementara dalang besar tak pernah benar-benar tersentuh.
Suara Jalanan Adalah Suara Kita
Demonstrasi bukanlah sekadar kerumunan. Ia adalah bahasa rakyat. Ketika jalur aspirasi resmi buntu, jalanan menjadi panggung terakhir untuk menyuarakan keresahan.
Mereka yang turun ke jalan bukanlah musuh negara. Mereka adalah anak-anak bangsa yang masih percaya bahwa suaranya bisa mengubah keadaan. Mereka adalah rakyat yang berani, meski tahu risiko berhadapan dengan aparat bersenjata.
Namun, apa balasan yang mereka terima? Gas air mata, pukulan, peluru karet, bahkan kematian.
Apakah ini wajah negara hukum yang kita banggakan? Apakah ini warisan yang akan kita titipkan kepada generasi selanjutnya?
Komnas HAM Mendesak Pertanggungjawaban
Komnas HAM menegaskan bahwa negara wajib menghentikan praktik sewenang-wenang, mengusut dugaan kekerasan aparat, dan menjamin proses hukum yang adil. Nyawa yang telah melayang tidak bisa kembali, tetapi kebenaran dan keadilan harus ditegakkan agar tidak ada lagi warga yang mati sia-sia.
Namun, pertanyaan terbesar masih sama: apakah hasil investigasi ini benar-benar akan ditegakkan, atau hanya akan menjadi laporan tebal yang berdebu di meja para penguasa?
Sejarah bangsa ini mencatat, terlalu banyak tragedi rakyat yang hanya menjadi arsip kelam, tanpa pernah ada keadilan yang benar-benar hadir. Jangan sampai tragedi 25 Agustus menjadi satu lagi catatan yang dilupakan.
Refleksi Moral: Negara untuk Siapa?
Tragedi ini kembali mengetuk kesadaran kita: untuk siapa negara ini ada? Apakah untuk rakyat kecil yang berjuang mencari keadilan, atau hanya untuk elityang menikmati kekuasaan?
Jika negara benar-benar ada untuk rakyat, maka seharusnya rakyat tidak mati di tangan aparatnya sendiri. Jika hukum benar-benar ditegakkan, maka setiap pelanggaran harus diadili tanpa pandang bulu. Jika demokrasi benar-benar hidup, maka suara rakyat tidak dibungkam dengan kekerasan.
Nyawa manusia bukan angka statistik. Ia adalah kehidupan, ia adalah doa, ia adalah harapan. Dan setiap darah yang tumpah tanpa keadilan akan menjadi utang sejarah yang tidak pernah lunas.
Saya menulis ini bukan sekadar sebagai pengurus organisasi, bukan pula sekadar sebagai seorang mahasiswa. Saya menulis ini sebagai bagian dari rakyat, yang merasa terlukai oleh tragedi kemanusiaan yang terjadi di depan mata.
Tragedi 25 Agustus harus menjadi pengingat keras: bahwa negara tidak boleh lagi mengulang kesalahan yang sama. Bahwa nyawa rakyat harus dihargai lebih tinggi daripada stabilitas politik sesaat. Bahwa hukum harus benar-benar berdiri tegak, bukan hanya untuk melindungi penguasa, tapi juga untuk melindungi rakyat kecil.
Karena sekali lagi, satu nyawa pun terlalu mahal untuk dikorbankan.
Penulis: Mudrika (Wakil Sekretaris Umum PP IPNU)
Editor: Salman